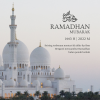Budaya Literasi di Tengah Arus Informasi Digital
Saat
penulis sedang membaca koran di perpustakaan sekolah, rekan penulis nyeletuk,
“perasaan saya, hanya sampean yang baca koran di sekolah kita. Memangnya masih
banyak orang membaca koran di jaman internet saat ini?”
Lalu saat itu juga penulis jadi ingat
pada sebuah lagu Jawa yang sedang hits. Judulnya “mendung tanpo udan”, tidak ada hubungannya dengan koran yang sedang
kami diskusikan pada saat itu. Tapi, lagu itu memuat lirik tentang mimpi di
masa depan sepasang kekasih, “Awak
dewe tau duwe bayangan
- Besok yen wes wayah omah-omahan - Aku
moco koran sarungan - Kowe blonjo dasteran – Kita pernah punya
bayangan - Besok kalau sudah berumah tangga - Aku membaca koran sarungan , kamu
belanja dasteran”.
Ternyata, pagi-pagi membaca koran
bagi sebagian orang tetap menjadi “sesuatu” yang mewah dan simbol kemapanan.
Karena lagu di atas bukan lagu lawas, maka keberadaan internet tidak akan serta
merta menenggelamkan keberadaan koran di dunia informasi. Terbukti, simbol
kemapanan kegiatan di pagi hari adalah membaca koran sambil ditemani secangkir
kopi atau teh.
Apa faktanya saat pagi hari orang
masih punya waktu untuk membaca koran
kertas? Faktanya, jumlah koran makin sedikit. Menurut catatan Dewan Pers, di
bulan Juni tahun 2021 ada tidak kurang dari 43 ribu media online di Indonesia.
Itu artinya, pembaca koran “konvensional” kian menyusut dan orang beralih ke
media online. Namun, menurut AC Nielsen di awal tahun 2021 menunjukkan trend bertumbuhnya pembaca koran,
terutama pada koran-koran besar, seperti Jawa Pos, Kompas, Pikiran Rakyat dan
beberapa koran besar lainnya. Sehingga perusahaan persuratkabaran memiliki
keyakinan bahwa “ koran akan terus ada sebagai pemenuhan atas kebutuhan penting
hidup bermasyarakat”.
Penulis yakin koran memiliki pangsa
pasar fanatiknya. Kalaupun ada penurunan jumlah pembaca koran kertas, namun
tidak akan pernah lenyap dari muka bumi selama ada kehidupan. Jelas koran
memiliki beberapa kelebihan, meski tetap juga memiliki kelemahan. Membaca koran
terasa lebih santai dan memiliki lapang pandang baca yang luas. Saat membaca
koran kita tidak akan khawatir kehabisan kuota internet sehingga bisa membaca
berita sampai tuntas.
Tradisi
membaca di masyarakat kita, harus diakui
masih rendah. Lemahnya budaya literasi berpangkal pada belum optimalnya gerakan
literasi dikalangan pelajar. Ditengah hegemoni informasi digital, pelajar di
negeri ini semakin jarang membaca bacaan berkualitas. Perpustakaan sekolah
lebih sering kosong dari kunjungan peserta didik. Peserta didik hanya akan
mengunjungi perpustakaan bila ada tugas sekolah yang memerlukan referensi
bacaan dari buku yang ada diperpustakaan. Berdasarkan hasil studi PISA (Programme for International Student Assessment) tahun
2018, skor Indonesia untuk kemampuan membaca masih berada
di level rendah, yaitu 371. Peringkat pertama untuk kemampuan membaca
ini diraih oleh China dengan skor 555. PISA merupakan sistem penilaian secara
internasional yang menitikberatkan pada kemampuan anak usia 15 tahun dalam
bidang literasi membaca, literasi matematika, dan literasi di bidang sains.
Baru-baru ini Kementrian Pendidikan
dan Kebudaayaan, Riset dan Teknologi melakukan Asesmen Nasional Berbasis
Komputer (ANBK) atau Asesmen Kompetensi Minimal (AKM) mulai dari tingkatan SD
sampai SMA sederajat. Hasilnya asesmen tersebut belum dirilis ke publik karena
kegiatannya belum berakhir. Salah satu tujuan asesmen tersebut adalah memetakan
kemampuan literasi dan numerasi pelajar Indonesia. Penulis memiliki
kekhawatiran terhadap hasil asesmen tersebut yang akan menjadi pembenar rendahnya
kemampuan literasi dan numerasi pelajarar kita secara nasional.
Perlu langkah-langkah strategis
menumbuhkan kembali budaya baca dimasyarakat kita, khususnya di kalangan
pelajar. Pelajar kita saat ini, minim sekali minat membacanya –kalau tidak mau
dikatakan musnah. Mereka (remaja/pelajar), terjerat jebakan game online dan medsos
yang adiktif, seperti Tik Tok, Youtube, Whatsapp, Instagram, Facebook, atau sederet permainan online.
Remaja kita saat ini sangat produktif menulis dan membaca hanya di ruang media
sosial. Bisa ditanya, sudah berapa buku yang mereka baca dalam sebulan
terakhir? Atau, dalam setahun ini pernahkah membaca artikel di koran atau
majalah? Jawabannya bisa ditebak, pasti sebagian besar nihil.
Meski tak mudah, merestorasi budaya
baca di masyarakat penulis yakin bisa
dilakukan. Mulai dari keluarga, sekolah, komunitas peduli membaca, dan
pemerintah. Sinergi dari semua elemen sangat diperlukan untuk mengembalikan
budaya baca di masyarakat. Dimulai dari pembiasaan di keluarga, misalnya orang
tua menyediakan buku-buku yang menarik untuk dibaca anak-anak dan remaja di
rumah. Upaya revitalisasi fungsi perpustakaan sekolah dan perpustakaan umum
perlu terus dilakukan. Perpustakaan jangan hanya sekedar menjadi tempat membaca
dan meminjam buku, tapi harus didesain ulang agar menjadi tempat yang nyaman
baik untuk membaca maupun kegiatan literasi yang lain, misal diskusi, bedah
buku, atau pameran buku.
Dalam membangun budaya literasi yang positif di sekolah,
terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah: mengkondisikan lingkungan fisik ramah
literasi, mengupayakan lingkungan sosial dan afektif, mengupayakan sekolah
sebagai lingkungan akademis yang literat. Implementasi dari strategi itu antara
lain dengan memajang karya peserta didik di semua area sekolah dan diganti
secara rutin. Akses yang mudah terhadap
bahan bacaan bagi semua peserta didik tidak hanya di perpustakaan, tapi juga
melalui sudut baca di ruang-ruang kelas. Pemberian penghargaan kepada peserta
didik terhadap capaian literasi adalah bagian penting untuk terus menumbuhan
minat literasi di kalangan peserta didik, misalnya melalui festival buku, lomba
mendongeng, atau lomba menulis cerita pendek. Juga, sekolah harus menyediakan
waktu yang cukup untuk menumbuhkan budaya literasi. Misalnya, mewajibkan semua
mata pelajaran untuk menyediakan waktu 10 menit untuk membaca buku pelajaran
sebelum pelajaran dimulai.
Optimisme akan terus berkembangnya budaya
literasi di kalangan peserta didik harus terus ditumbuhkan. Pasalnya pemerintah
sangat concern dengan upaya
peningkatan kompetensi literasi dan numerasi di kalangan peserta didik.
Berbagai program sudah dijalankan oleh pemerintah untuk mendongkrak kemampuan
literasi di kalangan peserta didik. Hal yang sama juga banyak dilakukan oleh
lembaga swadaya masyarakat untuk memantik nyala budaya literasi dikalangan
generasi muda. Arus informasi digital memang tidak bisa dicegah, namun harus
diimbangi dengan peningkatan kemampuan literasi masyarakat yang dimulai dari
generasi mudanya. Harapannya, kecerdasan literasi masyarakat bisa memfilter
mereka dari informasi-informasi yang tidak berdasarkan fakta (hoax). Semoga ! (Wahyudi Oetomo, S.Pd.)
*)
Penulis guru SMPN 1 Kamal